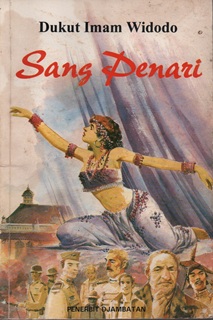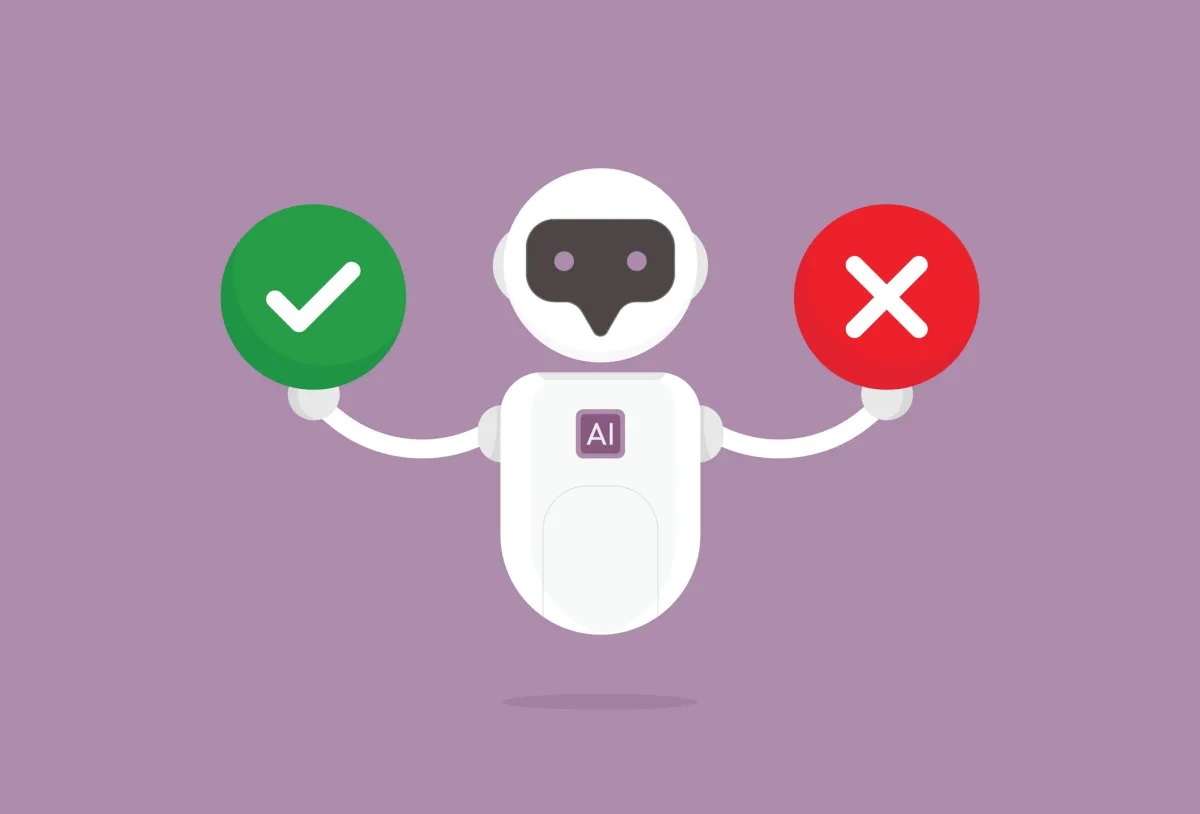Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan konsentrasi pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Selama menjalani studi, saya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik intra maupun ekstra kampus, sebagai bagian dari proses pengembangan kapasitas diri dan kontribusi sosial. Dalam ranah organisasi intra kampus, saya terlibat di Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Bimbingan dan Penyuluhan Islam, khususnya di Departemen Keislaman. Keterlibatan ini memberi saya ruang untuk memperkuat pemahaman keagamaan dan nilai-nilai dakwah yang inklusif di lingkungan akademik. Di luar struktur organisasi kampus, saya merupakan kader aktif Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Komisariat UIN Jakarta dan saat ini mengemban amanah sebagai Bendahara Umum. Peran ini memperluas wawasan saya dalam advokasi sosial serta gerakan mahasiswa berbasis ideologi kerakyatan dan nasionalisme. Selain itu, saya juga cukup aktif dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (Kompak), sebuah forum yang berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk kekerasan, baik dalam lingkup kampus maupun masyarakat luas. Keterlibatan saya dalam berbagai organisasi ini merupakan bentuk komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan dalam praktik nyata kehidupan mahasiswa.
Kita Tidak Butuh Negara dan Tuhan yang Diperjualbelikan
4 jam lalu
Sebuah seruan anarkis melawan hukum negara dan dogma agama yang menindas dan melahirkan kedunguan.
***
Tulisan ini muncul akibat kegelisahan yang dilihat dari serangkaian peristiwa yang menunjukkan betapa dalamnya kebusukan di negeri ini.
Aku melihat para santri turun ke jalan, mengepung gedung Trans 7, yang kemudian Transmart pun diikutsertakan menjadi target atas kemarahan mereka yang begitu besarnya karena tayangan yang dianggap menghina pesantren. Padahal pihak Trans 7 sudah meminta maaf. Tayangan itu hanya menampilkan satu pesantren yang memang secara objektif memperlihatkan subkultur di pesantren berupa praktik feodalisme di mana kyai dipuja bak raja, santri merendahkan diri bak abdi. Tapi yang terjadi justru pembelaan membabi buta.
Lalu, aksi yang diselenggarakan oleh Forum Santri Nusantara Bandung Raya, membawa isu dari pesantren Al-Khoziny yang rubuh karena bangunan tidak sesuai standar, mereka bukan menuntut keadilan dari pengelola, melainkan menuntut APBN untuk membangun kembali bangunan yang mereka sendiri salah kelola. Tuntutan demi tuntutan bermunculan, banyak di antaranya tidak masuk akal, sementara di waktu yang sama, mereka diam membisu terhadap kasus korupsi dana haji, bungkam saat mendengar pencabulan di pesantren, dan menutup mata ketika kekerasan terjadi di dalam pesantren.
Di sisi lain, ada 11 pejuang lingkungan dari masyarakat adat Maba Sangaji di Maluku Utara yang berjuang mempertahankan tanah mereka dari pencemaran tambang. Mereka bukan pencari sensasi, bukan perusuh, tapi penjaga bumi tempat mereka hidup. Namun, apa yang dilakukan negara? Bukan memberi penghargaan, tapi vonis bersalah dijatuhkan lewat Pengadilan Negeri Soasio. Sementara korporasi yang merusak lingkungan tetap berjalan tanpa hambatan.
Dari sanalah aku sadar kerusakan di tubuh negeri ini semakin dalam. Sepertinya ada yang salah dalam cara kita beragama, bernegara, dan berakal.
Negara ini berdiri gagah di atas lumpur ketidakadilan. Ia menuntut rakyatnya patuh dan mencintainya, padahal cinta sejati tidak pernah lahir dari keterpaksaan. Di hadapan hukum, kita diajarkan bahwa semua manusia sama, namun di ruang sidang, keadilan hanya milik mereka yang punya kekuasaan dan uang. Rakyat kecil digilas aturan, sementara para pejabat yang merampok uang rakyat justru disambut dengan tepuk tangan dan karpet merah.
Negara ini berdiri di atas hukum yang bukan lagi tentang keadilan, tapi kepatuhan. Hukum dibuat untuk menakut-nakuti rakyat kecil, sementara para penguasa mempermainkannya demi keuntungan pribadi. Mereka berbicara tentang moral, tapi menindas tanpa malu. Mikhail Bakunin, seorang anarkis besar abad ke-19, pernah menulis “Selama negara ada, tidak ada kebebasan; ketika kebebasan hidup, negara mati.” Kata-kata itu kini terasa seperti refleksi bagi Indonesia. Rakyat patuh bukan karena sadar, tapi karena takut. Kita membayar pajak, mengikuti aturan, dan diam saat diinjak. Semua karena kita telah diajari bahwa patuh adalah bentuk cinta pada negara.
Hukum di negeri ini bukanlah dewi keadilan, tapi rantai pengekang. Ia tidak lahir dari kesadaran moral, melainkan dari rasa takut. Ketika kita patuh bukan karena kita paham, melainkan karena kita takut, maka hukum telah gagal menjadi nilai, dan berubah menjadi alat penaklukan. Mikhail Bakunin juga pernah menulis bahwa “Negara adalah kekuasaan yang memaksa manusia untuk tunduk kepada hukum yang tidak pernah mereka ciptakan.” Kata-kata itu terasa hidup hari ini. Kita tunduk pada sistem yang kita tak pernah pilih, tapi ditanamkan seolah itu adalah takdir.
Lalu, negara memaksa kita untuk mencintainya dengan doktrin “Nasionalisme”. Tapi nasionalisme macam apa yang membiarkan rakyatnya lapar dan bodoh? Sekolah yang rusak, guru yang dibayar murah, anak-anak miskin yang dipaksa bermimpi di bawah bangunan yang nyaris rubuh. Kewajiban negara untuk menjamin pendidikan hanya menjadi slogan politik lima tahunan. Sementara itu, rakyat disuruh bangga dengan bendera dan lagu kebangsaan, padahal hidupnya sendiri diabaikan.
Nasionalisme yang dipaksakan hanya melahirkan kepatuhan buta. Sekolah diajarkan untuk memuja simbol, bukan berpikir kritis. Pendidikan seharusnya membebaskan, tapi justru menjadi alat untuk mencetak pekerja yang patuh, bukan manusia yang sadar. Presiden dan pejabat berbicara tentang kesejahteraan, tapi rakyat tetap menjadi sapi perah, anak-anak mereka diberi makan agar kemudian terbentuk dikepala mereka bahwa presiden begitu mulianya, padahal nyatanya orang tua mereka diperah lewat pajak, utang, dan sistem yang menindas.
Sementara agama, yang seharusnya menjadi pelipur lara, kini menjadi sumber perpecahan. Golongan sana menghina golongan sini, yang satu merasa paling benar, yang lain dituduh sesat. Leo Tolstoy mengungkapkan dalam karyanya “Agama sejati tidak memisahkan manusia, tetapi menyatukan mereka dalam cinta.” Namun di negeri ini, agama dijadikan bendera perang. Ia dijual untuk kepentingan politik, dijadikan alat pembenaran bagi keserakahan dan kekerasan. Dari mimbar ke media sosial, agama berubah menjadi pasar yang kemudian Tuhan diperjualbelikan dengan harga murah, hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh.
Negara dan agama kini berjalan bergandengan tangan, satu menindas tubuh, satu menawan jiwa. Negara memaksa tunduk pada hukum buatan elit sementara agama memaksa taat pada tafsir yang menguntungkan golongan tertentu. Keduanya mengajarkan ketakutan, bukan kesadaran. Dan manusia dibiarkan hidup dalam ketaatan yang kosong, tanpa kebebasan berpikir dan mencinta.
Maka aku sampaikan kepada kalian bahwa di sinilah anarkisme dapat menjadi napas pembebasan. Anarkisme bukan tentang kekacauan. Ia bukan ajakan untuk menghancurkan, melainkan kesadaran untuk mengorganisir diri tanpa harus hidup di bawah bayang-bayang otoritas penguasa. Peter Kropotkin, dalam suatu karyanya telah membuktikan bahwa kehidupan sosial tidak memerlukan negara untuk bertahan. Manusia, kata Kropotkin, secara alami hidup dari solidaritas, bukan kompetisi. “Bukan perang yang membuat manusia bertahan, melainkan kerja sama.”
Dalam anarkisme kita diajarkan untuk menolak kekuasaan yang lahir dari paksaan. Ia percaya bahwa manusia bisa hidup setara tanpa tuan dan budak, tanpa pejabat dan rakyat, tanpa kyai dan santri yang dipisahkan oleh feodalisme spiritual.
Anarkisme bukan anti-Tuhan, tapi menolak mereka yang menjual nama Tuhan untuk menindas sesama. Bukan anti agama, tapi menolak dogma agama yang melahirkan kebencian, penindasan, dan keterpaksaan. Ia adalah jalan menuju kesadaran bahwa moralitas sejati lahir dari cinta, bukan dari perintah.
Tolstoy menyebut keadaan itu sebagai “kerajaan Tuhan dalam hati manusia” — ketika manusia hidup dalam kebenaran batin tanpa perlu negara atau lembaga agama yang mengatur.
Kita tidak butuh negara yang memperlakukan rakyat seperti ternak. Kita tidak butuh agama yang sibuk mengadili iman orang lain. Kita tidak butuh hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kita butuh adalah kesadaran. Kesadaran untuk menjadi manusia yang bebas, yang berpikir, yang menolak tunduk pada ketakutan dan kebodohan yang dilegalkan.
Karena kita tidak butuh negara yang menjinakkan, tidak butuh Tuhan yang diperjualbelikan. Yang kita butuh adalah manusia yang sadar, yang paham bahwa cinta, solidaritas, dan kebebasan adalah hukum tertinggi kehidupan.
Dan pada hari ketika kesadaran itu hidup, baik negara maupun agama tidak lagi menjadi rantai, melainkan hanya kenangan dari masa ketika manusia pernah lupa menjadi manusia.
Penulis Indonesiana
1 Pengikut

Revolusi! Tak Ada Jalan Tengah!
Kamis, 4 September 2025 09:38 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





 99
99 0
0